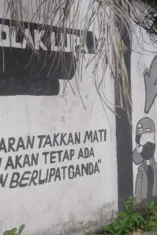Dunia pendidikan, yang seharusnya menjadi taman yang aman bagi anak-anak, kembali tercoreng. Rifki Ananda, seorang siswa kelas 6 SDN 021 Pematang Raman, diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh gurunya sendiri, Tri Wulandari.
Jika awalnya dugaan ini dianggap sebagai “kesalahpahaman”, kini kebenaran berbicara melalui hasil visum: terdapat luka di bibir Rifki akibat benda tumpul dan keluhan sakit kepala yang dideritanya.
Ini bukan lagi sekadar tuduhan. Ini adalah fakta medis. Fakta bahwa Rifki mengalami luka fisik dan trauma, memperkuat keyakinan bahwa kekerasan benar-benar terjadi di ruang yang seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter, bukan perusakan martabat.
Dalam perspektif hukum, kasus ini sudah memenuhi unsur pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam:
Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:
“Setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.”
Dan juga:
Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan:
“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, atau denda.”
Keluhan sakit kepala Rifki mempertegas bahwa dampak kekerasan ini tidak hanya luka luar, tetapi juga potensi luka internal yang perlu dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
Pertanyaannya sederhana: apakah kekerasan terhadap anak bisa dimaafkan hanya dengan alasan “kesalahpahaman” atau “emosi sesaat”?
Jawabannya: tidak.
Tidak dalam konteks etika. Tidak dalam konteks hukum.