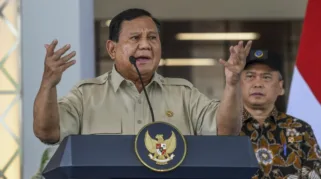Dahulu tasawuf itu belum seperti yang kita pahami sekarang, tasawuf bukan sistem tarekat, bukan teori metafisika yang kompleks. Perkembangan awalnya lebih ke zuhud (menjauhkan diri dari dunia), sederhana, spiritualitas praktis. Orang‑orang seperti Sahabat, Tabi’in, terus ke tokoh‑zuhud awal seperti Hasan al‑Basri tampil sebagai panutan. Hasan mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanya jembatan untuk melewatinya, bahwa zuhud bukan berarti melarikan diri dari dunia sepenuhnya, tapi hati jangan tergantung pada kemewahan, harus selalu ada rasa takut (khauf), harap (raja’), dan tawakkal.
Hemat saya Ahmed Zidan Saputra, masa tasawuf sebelum Al‑Ghazali justru sangat otentik. Walau belum tersusun secara sistematis, tapi spiritualitasnya sangat jujur dan hidup. Mereka tidak terlalu pusing soal teori atau label, yang diutamakan adalah kedekatan dengan Allah dan bersih dari dunia. Dalam kesederhanaan itu, justru ada ketulusan yang kuat, dan saya rasa itu yang kadang kita lupakan di zaman sekarang.
Pada masa abad ke‑2 sampai ke‑4 H, tasawuf mulai berkembang dari amalan asketik menuju pemikiran yang lebih teoritis, psikologis, dan akhlaki. Para sufi mulai memikirkan bagaimana jiwa atau moral bisa dibersihkan, bagaimana pengalaman batiniah mendekatkan diri ke Allah, bukan cuma rutinitas ibadah saja. Tokoh‑tokoh seperti Junaid al‑Baghdadi, Al‑Hallaj, Abu Yazid al‑Bistami adalah contoh yang mulai memainkan aspek pengalaman mistik, ekstasi, penghayatan rasa dalam ibadah.
Kemudian datanglah Al‑Ghazali (lahir 450 H /1057 M). Beliau semacam titik balik dalam sejarah tasawuf Islam. Kenapa? Karena pada zamannya banyak aliran yang mulai melebar kepada hal-hal yang dianggap menyimpang: panteisme, hulul (pemahaman bahwa Tuhan “turun” ke ciptaan secara literal), wahdatul wujud (bahwa wujud semua adalah Tuhan; yang lain hanya ilusi), dan penggabungan filsafat Yunani secara bebas. Beberapa ulama dan fuqaha mulai khawatir bahwa tasawuf akan kehilangan akar pribadinya dalam Qur’an dan Sunnah.