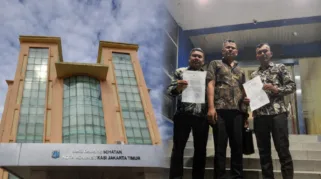Apa kabar akal sehat kita hari ini? Barangkali sedang cuti panjang, bersama logika publik yang terus diacak-acak oleh kekuasaan. Kasus Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku adalah episode terbaru dari sinetron panjang berjudul “Negara Absen, Hukum Bungkam, Kekuasaan Tertawa”.
Ketika Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto, kita seolah diajak bermain teater. Tapi ini bukan teater yang memperkaya batin seperti “Hamlet” atau “Antigone”. Ini teater politik murahan, di mana aktor utama memerankan diri sebagai korban, sementara penonton dipaksa percaya bahwa skenarionya logis.
Amnesti atau Alibi Politik?
Amnesti, dalam tradisi politik modern, adalah mekanisme rekonsiliasi. Tapi kali ini, amnesti jadi alibi. Harusnya diberikan untuk mereka yang terlibat konflik politik, bukan mereka yang terjebak dalam pusaran transaksi kekuasaan. Tapi begitulah: definisi bisa diutak-atik jika yang berbicara adalah kekuasaan. Semantik tunduk pada narasi penguasa.
Hasto didakwa menyuap Komisioner KPU untuk menyelundupkan Harun Masiku ke parlemen. Harun sendiri adalah buron yang entah ada di mana—mungkin di negeri dongeng, mungkin di balik tirai kekuasaan. Tapi anehnya, justru orang yang tahu ke mana Harun pergi dimaafkan. Ini seperti membebaskan sopir bajaj yang membawa kabur dompet kita, sambil berkata: “Ah, dia hanya supirnya, yang maling penumpangnya.”
Logika semacam ini cuma bisa hidup dalam negara yang membiarkan akal sehat mati.
Hukum Dibajak Kekuasaan
Kasus ini memperlihatkan bahwa hukum bukan lagi alat mencari keadilan, tapi instrumen kekuasaan untuk membungkam kegaduhan. Lembaga seperti KPK dipaksa bermain di atas papan catur yang catur-nya sudah diatur. Mereka tidak lagi mengejar keadilan, tapi hanya memelihara ilusi bahwa keadilan masih dikejar.
Padahal, obstruction of justice—perintangan penyidikan—adalah pintu masuk untuk membongkar lebih besar. Tapi dengan amnesti ini, pintu itu dikunci dari luar. Pertanyaannya: siapa yang pegang kuncinya?
Negara Sedang Tak Ada
Dalam filsafat politik klasik, negara adalah wasit. Tapi dalam kasus ini, negara bahkan tidak hadir sebagai penonton, apalagi wasit. Ia cuma jadi panggung kosong yang dipakai elite untuk berdialog dengan egonya sendiri. Sementara publik? Ya seperti biasa, dipaksa menonton, dipaksa percaya, dan pada akhirnya dipaksa lupa.
Kita sekarang berada dalam situasi yang oleh Gramsci disebut “interregnum”: kekuasaan lama belum mati, kekuasaan baru belum lahir, dan yang berkuasa adalah kekacauan.
Akal Sehat Adalah Oposisi Terakhir
Jika hukum bisa dinegosiasikan, dan pengampunan bisa dijadikan alat tawar-menawar politik, maka hanya satu hal yang tidak boleh dikorbankan: akal sehat. Dan di republik yang sedang kehilangan moral publik ini, satu-satunya oposisi yang tersisa adalah logika publik yang masih berani berpikir.
Hasto dibebaskan. Harun masih kabur. Negara absen. Tapi setidaknya, kita belum kehilangan kemampuan untuk muak.