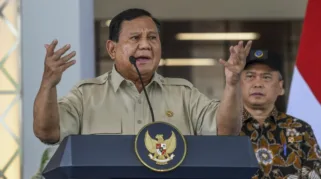DPR itu, secara teori, adalah rumah rakyat. Tetapi dalam praktiknya, ia lebih mirip rumah kaca: dari luar tampak megah, dari dalam penuh bayangan kepentingan. Publik melihat wakilnya duduk di kursi empuk, tetapi suara rakyat sendiri dipantulkan kembali sebagai gema kosong. Itulah ironi.
Apa yang kita saksikan belakangan bukan sekadar demo yang ricuh, melainkan letupan nalar publik. Ketika pintu dialog ditutup rapat, jalanan menjadi forum terbuka. Rakyat masuk ke ruang politik bukan melalui undangan DPR, melainkan melalui teriakan di aspal.
Tragedinya jelas: seorang driver ojol dilindas mobil aparat. Ia bukan demonstran garis depan, ia hanya rakyat biasa yang sedang mencari nafkah. Ironis, kan? Negara yang katanya melindungi justru menindas. Aspal yang mestinya jadi ruang kerja seorang pencari nafkah berubah jadi liang lahat. Itu bukan kecelakaan, itu konsekuensi dari politik yang kehilangan akal sehat.
Lalu apa reaksi DPR? Setelah rumah mereka dijarah, mereka buru-buru minta maaf. Saya tersenyum getir. Itu artinya, permintaan maaf bukan lahir dari kesadaran, melainkan dari rasa takut. Mereka baru merasa menjadi rakyat setelah rumahnya diperlakukan seperti rakyat memperlakukan gedung DPR: tempat meluapkan amarah.
Permintaan maaf DPR itu seperti menyalakan lilin setelah rumah terbakar habis. Simbolik, tapi tidak menyelamatkan apa-apa. Rakyat tentu tidak membutuhkan sekadar kata maaf. Yang dibutuhkan adalah keberanian DPR mengembalikan politik pada akal sehat: membuka telinga, berdialog, dan berhenti memperlakukan rakyat sebagai objek kebijakan.
Kericuhan itu hanya gejala. Penyakitnya ada di DPR sendiri: lembaga yang kehilangan fungsi representasi. Selama itu tidak diobati, selama politik dijalankan dengan nafsu kuasa, bukan akal sehat, maka luka di aspal itu akan terus berulang.
DPR suka bicara tentang “kepentingan bangsa”, padahal yang mereka maksud sering kali hanya kepentingan partai. Bangsa itu ada di jalanan, di ojol yang terbunuh, di mahasiswa yang dipukul, di rakyat yang marah. Jika DPR lupa itu, maka mereka bukan lagi wakil rakyat, melainkan wakil dari kepentingan yang entah siapa.
Dan rakyat akan terus mengingat. Ingat bahwa negara pernah abai, ingat bahwa seorang pencari nafkah gugur di jalan, ingat bahwa politik bisa kehilangan akal sehat.