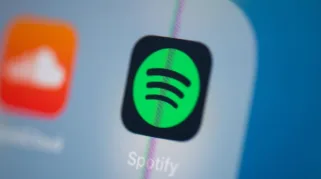Oleh: Feri Irawan
Ketua Sekber PSDH JAMBI
Menutup tahun 2025, Indonesia berdiri di hadapan satu pertanyaan mendasar untuk siapa sebenarnya negara mengelola tanah dan kawasan? Bagi jutaan warga desa yang hidup di sekitar dan di dalam wilayah berhutan, pertanyaan ini bukan diskursus akademik, melainkan pengalaman sehari-hari. Tanah yang diwariskan dari generasi ke generasi bisa sewaktu-waktu berubah status, bukan karena perubahan pada tanah itu sendiri, melainkan karena perubahan tafsir negara atas peta dan kawasan.
Restrukturisasi kelembagaan yang melahirkan Kementerian Kehutanan dan penguatan peran ATR/BPN semestinya menjadi momentum untuk mengakhiri konflik lama antara rezim kehutanan dan rezim pertanahan. Namun sepanjang 2025, yang terjadi justru sebaliknya. Percepatan sertipikasi tanah berjalan bersamaan dengan penguatan pengamanan kawasan. Dua agenda ini melaju di jalurnya masing-masing, tanpa jembatan kebijakan yang memadai. Rakyat kembali menjadi korban benturan antar-rezim.
Di atas kertas, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah simbol kehadiran negara. Ia menjanjikan kepastian hukum, membuka akses permodalan, dan memperkuat posisi ekonomi warga. Tetapi bagi banyak masyarakat desa sekitar kawasan, sertipikat bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari konflik baru. Hak yang telah diakui oleh negara melalui ATR/BPN bisa sewaktu-waktu dipersoalkan karena wilayahnya diklaim sebagai kawasan hutan. Negara seolah memberi dengan satu tangan dan menariknya kembali dengan tangan yang lain.
Masalah ini bukan persoalan teknis semata. Ia adalah persoalan paradigma. Kementerian Kehutanan masih membawa warisan cara pandang lama, ruang diperlakukan sebagai wilayah kuasa yang harus diamankan, bukan sebagai ruang hidup yang harus diakui. Sementara ATR/BPN mengusung mandat reforma agraria berbasis hak. Dua paradigma ini belum pernah benar-benar dipertemukan dalam satu kebijakan ruang yang koheren. Yang terjadi adalah koeksistensi yang rapuh, bukan integrasi yang bermakna.