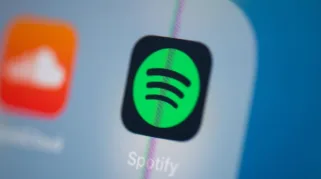Oleh: Feri Irawan
Ketua Sekber PSDH JAMBI
Menutup tahun 2025, Indonesia berdiri di hadapan satu pertanyaan mendasar untuk siapa sebenarnya negara mengelola tanah dan kawasan? Bagi jutaan warga desa yang hidup di sekitar dan di dalam wilayah berhutan, pertanyaan ini bukan diskursus akademik, melainkan pengalaman sehari-hari. Tanah yang diwariskan dari generasi ke generasi bisa sewaktu-waktu berubah status, bukan karena perubahan pada tanah itu sendiri, melainkan karena perubahan tafsir negara atas peta dan kawasan.
Restrukturisasi kelembagaan yang melahirkan Kementerian Kehutanan dan penguatan peran ATR/BPN semestinya menjadi momentum untuk mengakhiri konflik lama antara rezim kehutanan dan rezim pertanahan. Namun sepanjang 2025, yang terjadi justru sebaliknya. Percepatan sertipikasi tanah berjalan bersamaan dengan penguatan pengamanan kawasan. Dua agenda ini melaju di jalurnya masing-masing, tanpa jembatan kebijakan yang memadai. Rakyat kembali menjadi korban benturan antar-rezim.
Di atas kertas, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah simbol kehadiran negara. Ia menjanjikan kepastian hukum, membuka akses permodalan, dan memperkuat posisi ekonomi warga. Tetapi bagi banyak masyarakat desa sekitar kawasan, sertipikat bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari konflik baru. Hak yang telah diakui oleh negara melalui ATR/BPN bisa sewaktu-waktu dipersoalkan karena wilayahnya diklaim sebagai kawasan hutan. Negara seolah memberi dengan satu tangan dan menariknya kembali dengan tangan yang lain.
Masalah ini bukan persoalan teknis semata. Ia adalah persoalan paradigma. Kementerian Kehutanan masih membawa warisan cara pandang lama, ruang diperlakukan sebagai wilayah kuasa yang harus diamankan, bukan sebagai ruang hidup yang harus diakui. Sementara ATR/BPN mengusung mandat reforma agraria berbasis hak. Dua paradigma ini belum pernah benar-benar dipertemukan dalam satu kebijakan ruang yang koheren. Yang terjadi adalah koeksistensi yang rapuh, bukan integrasi yang bermakna.
Sepanjang 2025, publik kembali disuguhi kisah-kisah berulang, petani yang dikriminalisasi karena menggarap kebun keluarga, desa definitif yang dipetakan ulang, sertipikat yang dibatalkan atau ditunda pengakuannya. Semua ini menunjukkan satu gejala, negara tidak sepenuhnya percaya pada produk hukumnya sendiri. Sertipikat, yang seharusnya menjadi simbol tertinggi kepastian hukum, justru menjadi dokumen yang selalu berada dalam tanda tanya.
Untuk menambal luka ini, pemerintah menawarkan Tanah Objek Reforma Agraria dari pelepasan kawasan dan perhutanan sosial sebagai jalan tengah. Namun kedua skema ini lebih sering menjadi solusi administratif daripada solusi keadilan. TORA berjalan selektif dan lambat, terikat pada kepentingan politik dan teknokratis. Perhutanan sosial, meskipun membuka akses kelola, tidak pernah menjawab kebutuhan utama banyak komunitas pengakuan hak atas tanah.
Bagi masyarakat yang telah menguasai tanah selama puluhan tahun, pergeseran status dari pemilik menjadi pemegang izin adalah bentuk degradasi hukum. Ia mengubah relasi warga dengan negara, dari subjek pemilik hak menjadi objek penerima toleransi. Negara tidak lagi hadir untuk mengakui, tetapi untuk mengizinkan. Di sinilah letak paradoks kebijakan agraria hari ini.
Masalah ini diperparah oleh praktik penunjukan kawasan yang masih bertumpu pada peta lama. Validasi sosial sering kali dipahami sebagai formalitas, bukan substansi. Desa, wilayah adat, dan kebun rakyat diperlakukan sebagai gangguan administratif. Negara lebih percaya pada garis di peta daripada pada sejarah hidup masyarakat. Padahal, ruang bukan hanya entitas fisik, melainkan juga entitas sosial yang menyimpan relasi, identitas, dan memori kolektif.
Menyambut 2026, negara tidak lagi memiliki alasan untuk menunda koreksi. Konflik agraria bukan lagi anomali, melainkan gejala struktural. Ia lahir dari dualisme kebijakan yang terus dipelihara. Di satu sisi, negara menggaungkan reforma agraria. Di sisi lain, negara mempertahankan logika penguasaan kawasan yang mengabaikan hak warga.
Rekonstruksi kebijakan harus dimulai dari satu keberanian mendasar, menggeser paradigma dari penguasaan ke pengakuan. Penetapan kawasan harus melewati proses validasi sosial yang sungguh-sungguh, bukan sekadar pengumuman administratif. Sertipikat tanah harus diposisikan sebagai produk hukum final, bukan dokumen yang bisa dipatahkan oleh klaim sepihak. Negara tidak boleh terus hidup dalam kontradiksi antara memberi dan mencabut hak.
Perhutanan sosial pun perlu direposisi. Ia tidak boleh dijadikan substitusi reforma agraria. Ia harus berdiri sebagai skema pengelolaan bagi wilayah yang secara ekologis memang memerlukan perlindungan khusus, bukan sebagai alat untuk menurunkan status hak rakyat. Tidak semua konflik agraria membutuhkan izin, banyak di antaranya justru menuntut pengakuan kepemilikan yang selama ini diabaikan.
Pada akhirnya, refleksi menyambut 2026 ini mengarah pada satu pertanyaan politis, apakah negara masih ingin mempertahankan logika kolonial penguasaan ruang, atau mulai membangun tata kelola berbasis hak warga negara? Konflik agraria tidak akan pernah selesai jika negara terus berdiri di antara dua kepentingan tanpa keberpihakan yang jelas.
Indonesia tidak kekurangan regulasi. Yang kita kekurangan adalah keberanian untuk menata ulang relasi negara dan rakyat dalam pengelolaan ruang. Tahun 2026 harus menjadi titik balik. Jika tidak, maka sertipikat akan terus menjadi kertas rapuh, kawasan akan terus menjadi alat eksklusi, dan konflik agraria akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.