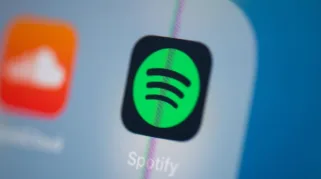Menyambut 2026, negara tidak lagi memiliki alasan untuk menunda koreksi. Konflik agraria bukan lagi anomali, melainkan gejala struktural. Ia lahir dari dualisme kebijakan yang terus dipelihara. Di satu sisi, negara menggaungkan reforma agraria. Di sisi lain, negara mempertahankan logika penguasaan kawasan yang mengabaikan hak warga.
Rekonstruksi kebijakan harus dimulai dari satu keberanian mendasar, menggeser paradigma dari penguasaan ke pengakuan. Penetapan kawasan harus melewati proses validasi sosial yang sungguh-sungguh, bukan sekadar pengumuman administratif. Sertipikat tanah harus diposisikan sebagai produk hukum final, bukan dokumen yang bisa dipatahkan oleh klaim sepihak. Negara tidak boleh terus hidup dalam kontradiksi antara memberi dan mencabut hak.
Perhutanan sosial pun perlu direposisi. Ia tidak boleh dijadikan substitusi reforma agraria. Ia harus berdiri sebagai skema pengelolaan bagi wilayah yang secara ekologis memang memerlukan perlindungan khusus, bukan sebagai alat untuk menurunkan status hak rakyat. Tidak semua konflik agraria membutuhkan izin, banyak di antaranya justru menuntut pengakuan kepemilikan yang selama ini diabaikan.
Pada akhirnya, refleksi menyambut 2026 ini mengarah pada satu pertanyaan politis, apakah negara masih ingin mempertahankan logika kolonial penguasaan ruang, atau mulai membangun tata kelola berbasis hak warga negara? Konflik agraria tidak akan pernah selesai jika negara terus berdiri di antara dua kepentingan tanpa keberpihakan yang jelas.