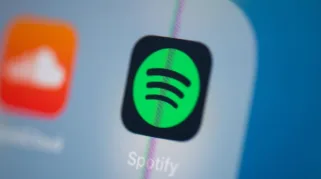Sepanjang 2025, publik kembali disuguhi kisah-kisah berulang, petani yang dikriminalisasi karena menggarap kebun keluarga, desa definitif yang dipetakan ulang, sertipikat yang dibatalkan atau ditunda pengakuannya. Semua ini menunjukkan satu gejala, negara tidak sepenuhnya percaya pada produk hukumnya sendiri. Sertipikat, yang seharusnya menjadi simbol tertinggi kepastian hukum, justru menjadi dokumen yang selalu berada dalam tanda tanya.
Untuk menambal luka ini, pemerintah menawarkan Tanah Objek Reforma Agraria dari pelepasan kawasan dan perhutanan sosial sebagai jalan tengah. Namun kedua skema ini lebih sering menjadi solusi administratif daripada solusi keadilan. TORA berjalan selektif dan lambat, terikat pada kepentingan politik dan teknokratis. Perhutanan sosial, meskipun membuka akses kelola, tidak pernah menjawab kebutuhan utama banyak komunitas pengakuan hak atas tanah.
Bagi masyarakat yang telah menguasai tanah selama puluhan tahun, pergeseran status dari pemilik menjadi pemegang izin adalah bentuk degradasi hukum. Ia mengubah relasi warga dengan negara, dari subjek pemilik hak menjadi objek penerima toleransi. Negara tidak lagi hadir untuk mengakui, tetapi untuk mengizinkan. Di sinilah letak paradoks kebijakan agraria hari ini.
Masalah ini diperparah oleh praktik penunjukan kawasan yang masih bertumpu pada peta lama. Validasi sosial sering kali dipahami sebagai formalitas, bukan substansi. Desa, wilayah adat, dan kebun rakyat diperlakukan sebagai gangguan administratif. Negara lebih percaya pada garis di peta daripada pada sejarah hidup masyarakat. Padahal, ruang bukan hanya entitas fisik, melainkan juga entitas sosial yang menyimpan relasi, identitas, dan memori kolektif.