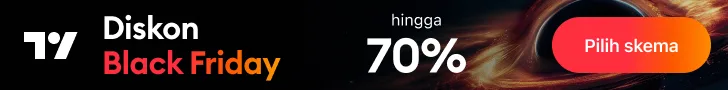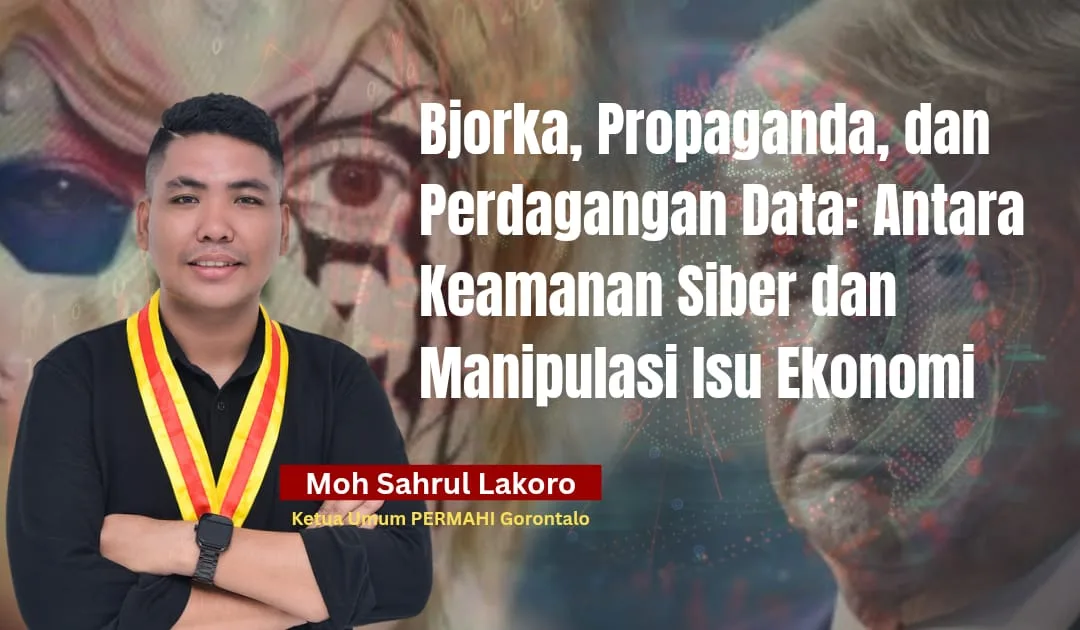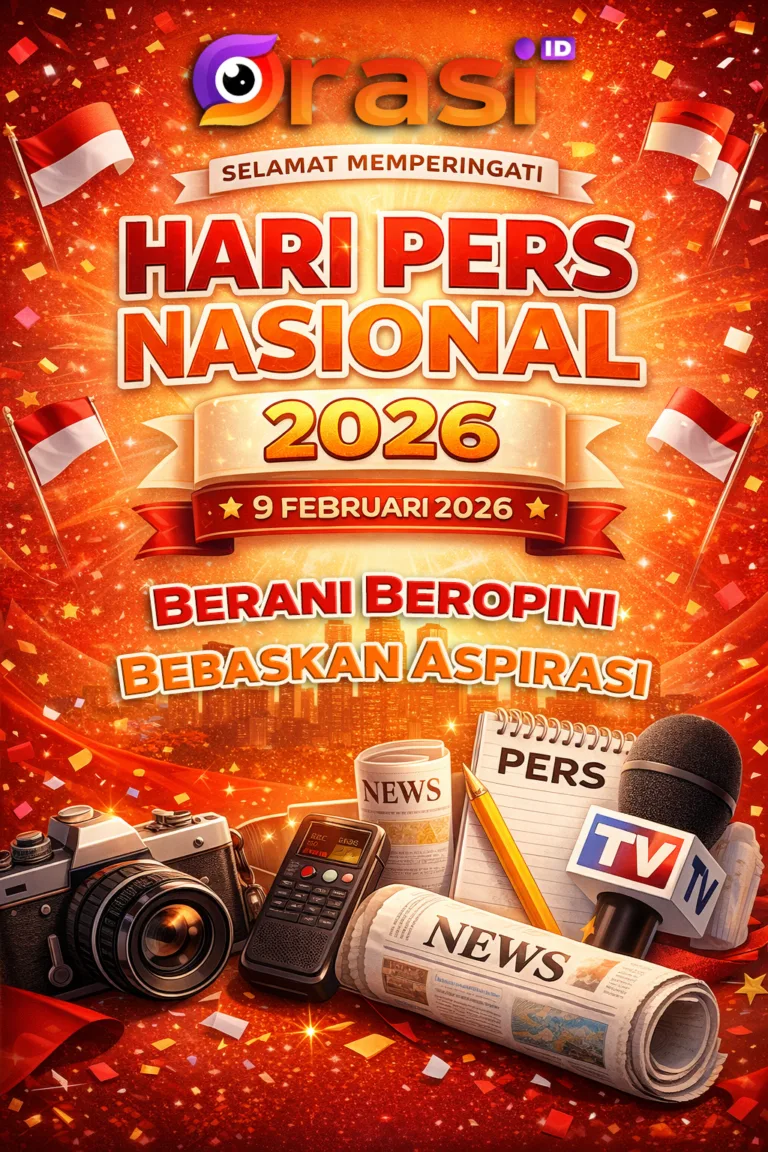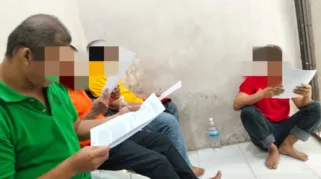Sejak 2022, pemerintah sudah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Namun hingga kini, penegakan hukumnya lemah, dan mekanisme audit forensik atas setiap kebocoran data nyaris tak pernah dipublikasikan. Kasus Bjorka hanya berakhir pada penangkapan beberapa individu, tanpa kejelasan siapa aktor utama di baliknya.
Jika pemerintah serius menjaga keamanan data, seharusnya audit independen dilakukan secara terbuka, bukan hanya melalui pernyataan pers atau konferensi singkat. Tanpa transparansi, isu keamanan akan terus menjadi alat politik, bukan instrumen perlindungan publik.
Kedaulatan Digital: Pilar Baru Kemerdekaan
Isu Bjorka membawa kita pada refleksi yang lebih mendasar: bahwa kedaulatan di abad digital tidak lagi hanya soal wilayah darat, laut, dan udara tetapi juga tentang ruang data. Data rakyat adalah representasi identitas, perilaku, dan kehidupan sosial yang tak ternilai. Ketika data itu diperdagangkan, maka sesungguhnya yang diperjualbelikan adalah privasi dan kendali atas warga negara itu sendiri.
Sayangnya, diskursus ini jarang muncul dalam ruang publik. Wacana digital di Indonesia masih didominasi oleh isu teknis dan keamanan, bukan isu kedaulatan dan etika. Pemerintah seolah ingin menunjukkan kemampuan mengatasi hacker, tetapi belum menunjukkan keseriusan menjaga hak digital warga negara.