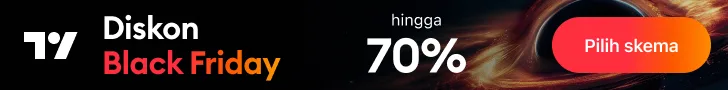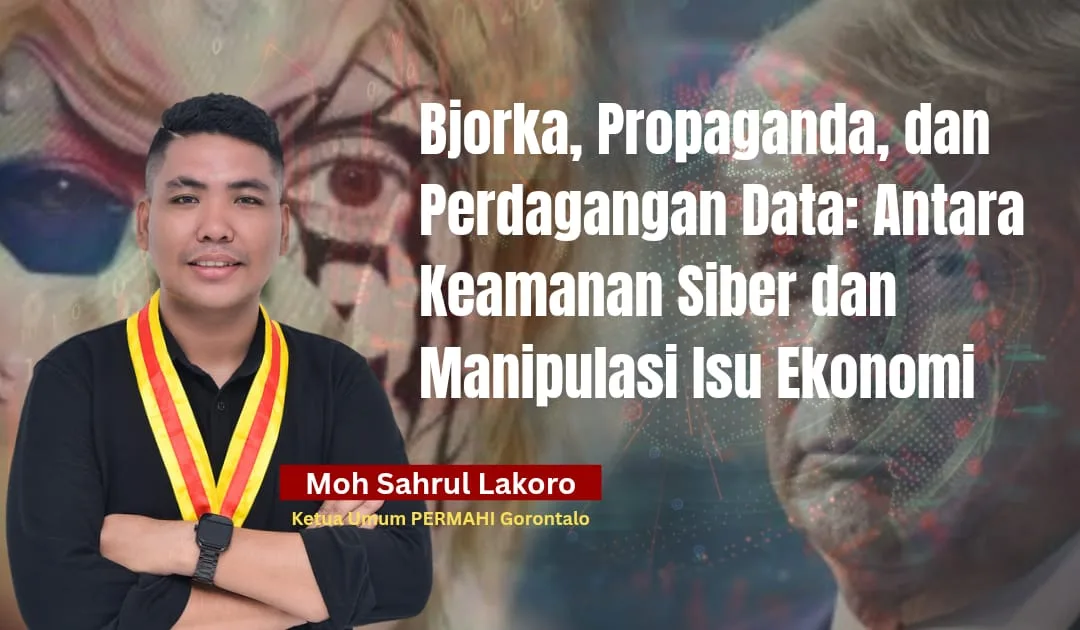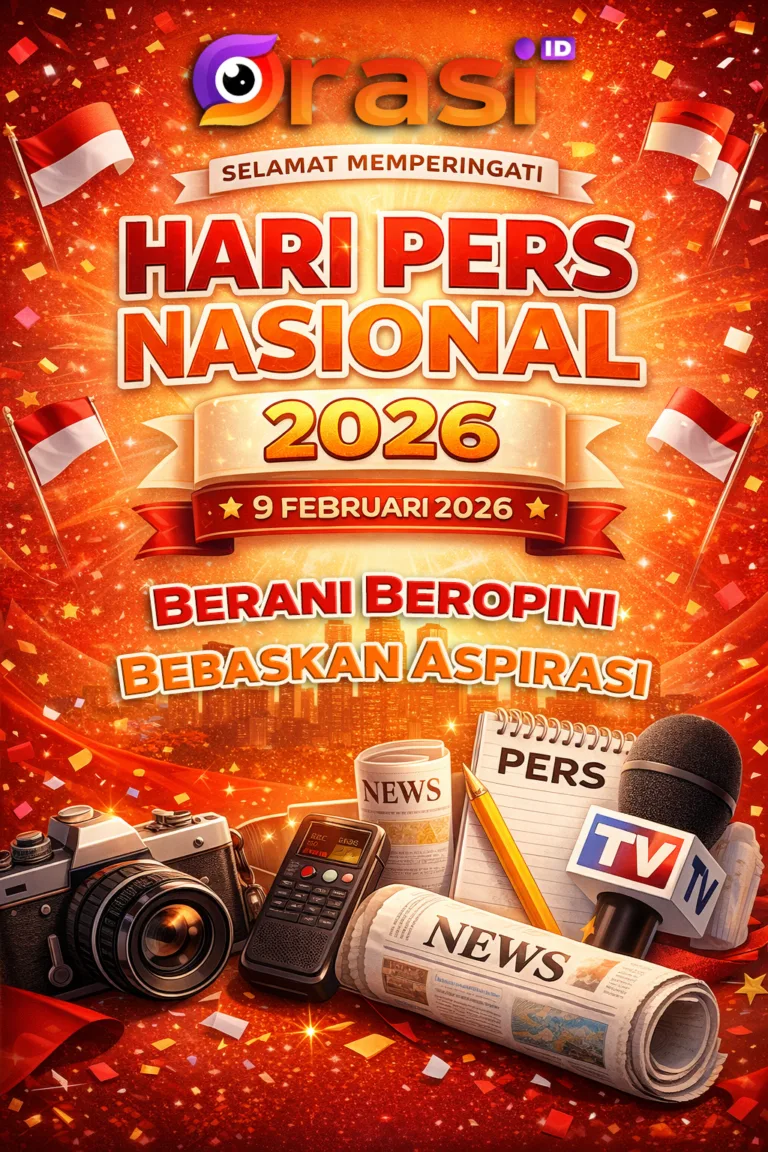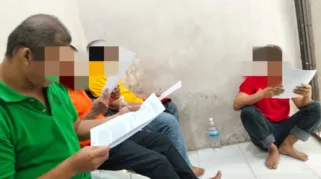Isu Bjorka: Antara Hacker dan Hegemoni
Dalam konteks ini, kemunculan Bjorka bisa dibaca sebagai pengalih perhatian strategis. Fokus publik diarahkan pada sosok misterius dan sensasi kebocoran data, sementara kebijakan strategis seperti perjanjian dagang lintas data berlangsung tanpa pengawasan kritis.
Kita seolah menyaksikan drama nasional: pemerintah tampil sebagai korban dan pahlawan sekaligus, sedangkan rakyat diarahkan untuk percaya bahwa solusinya adalah memperkuat kerja sama digital dengan negara lain. Padahal, kerja sama itu justru bisa membuka pintu bagi eksploitasi data rakyat oleh kekuatan asing.
Bentuk propaganda semacam ini bukan hal baru. Dalam kajian media, fenomena ini disebut manufacturing consent istilah yang dipopulerkan Noam Chomsky. Pemerintah dan media secara tidak langsung membentuk persetujuan publik melalui narasi ancaman dan ketakutan. Dalam kasus Bjorka, rasa takut terhadap hacker digunakan untuk menciptakan legitimasi kebijakan ekonomi yang tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat.
Ketika Keamanan Mengorbankan Kedaulatan
Pemerintah tentu berhak memperkuat keamanan siber. Tetapi keamanan tidak boleh menjadi dalih untuk melemahkan kedaulatan. Ironisnya, kebijakan yang lahir dari isu kebocoran data justru berpotensi memperbesar ketergantungan Indonesia terhadap sistem dan standar keamanan global yang dikendalikan negara-negara maju.