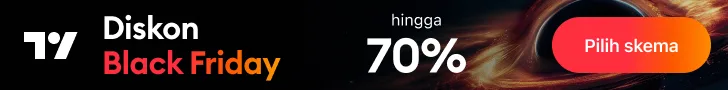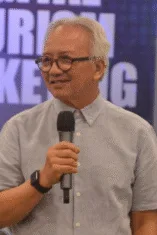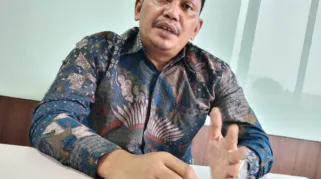Oleh: Ahmed Zidan Saputra, Mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam (S1), UIN STS Jambi
Dahulu tasawuf itu belum seperti yang kita pahami sekarang, tasawuf bukan sistem tarekat, bukan teori metafisika yang kompleks. Perkembangan awalnya lebih ke zuhud (menjauhkan diri dari dunia), sederhana, spiritualitas praktis. Orang‑orang seperti Sahabat, Tabi’in, terus ke tokoh‑zuhud awal seperti Hasan al‑Basri tampil sebagai panutan. Hasan mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanya jembatan untuk melewatinya, bahwa zuhud bukan berarti melarikan diri dari dunia sepenuhnya, tapi hati jangan tergantung pada kemewahan, harus selalu ada rasa takut (khauf), harap (raja’), dan tawakkal.
Hemat saya Ahmed Zidan Saputra, masa tasawuf sebelum Al‑Ghazali justru sangat otentik. Walau belum tersusun secara sistematis, tapi spiritualitasnya sangat jujur dan hidup. Mereka tidak terlalu pusing soal teori atau label, yang diutamakan adalah kedekatan dengan Allah dan bersih dari dunia. Dalam kesederhanaan itu, justru ada ketulusan yang kuat, dan saya rasa itu yang kadang kita lupakan di zaman sekarang.
Pada masa abad ke‑2 sampai ke‑4 H, tasawuf mulai berkembang dari amalan asketik menuju pemikiran yang lebih teoritis, psikologis, dan akhlaki. Para sufi mulai memikirkan bagaimana jiwa atau moral bisa dibersihkan, bagaimana pengalaman batiniah mendekatkan diri ke Allah, bukan cuma rutinitas ibadah saja. Tokoh‑tokoh seperti Junaid al‑Baghdadi, Al‑Hallaj, Abu Yazid al‑Bistami adalah contoh yang mulai memainkan aspek pengalaman mistik, ekstasi, penghayatan rasa dalam ibadah.
Kemudian datanglah Al‑Ghazali (lahir 450 H /1057 M). Beliau semacam titik balik dalam sejarah tasawuf Islam. Kenapa? Karena pada zamannya banyak aliran yang mulai melebar kepada hal-hal yang dianggap menyimpang: panteisme, hulul (pemahaman bahwa Tuhan “turun” ke ciptaan secara literal), wahdatul wujud (bahwa wujud semua adalah Tuhan; yang lain hanya ilusi), dan penggabungan filsafat Yunani secara bebas. Beberapa ulama dan fuqaha mulai khawatir bahwa tasawuf akan kehilangan akar pribadinya dalam Qur’an dan Sunnah.
Al‑Ghazali kemudian mencoba “membenahi” tasawuf kemudian menariknya kembali ke Qur’an dan Sunnah, menggabungkan antara syari’at (aturan lahiriah) dengan tasawuf (dimensi batiniah), dan menyaring unsur‑filsafat yang dianggap terlalu spekulatif. Karya monumental beliau Ihya Ulum al‑Din adalah contoh bagaimana tasawuf tidak hanya buat orang‑orang mistik saja tapi bisa jadi bagian dari hidup orang sehari‑hari, moral, ibadah, sosial.
Setelah Al‑Ghazali, perkembangan dan dampak tasawuf sangat luas. Tasawuf yang moderat makin diterima di kalangan ulama syariat (ahlu sunna wa jama’ah). Kritik terhadap praktik yang dianggap menyimpang makin sering muncul. Tasawuf dianggap tidak boleh bertentangan dengan syari’at; karya‑karya sufi yang ekstrem atau yang menggunakan istilah mistis yang bisa disalahartikan mulai dikaji ulang atau dikoreksi.
Tokoh‑tokoh setelah Al‑Ghazali ikut mengambil jalan ini: mereka menyeimbangkan antara aspek moral, batin, dan hukum. Juga, pengaruh Al‑Ghazali terasa sangat kuat di banyak wilayah Islam termasuk Asia Tenggara, di pesantren, tarekat, pendidikan karakter. Tasawuf bukan cuma dihormati sebagai jalan mistik, tapi sebagai bagian resmi pendidikan Islam di beberapa wilayah.
Hipotesis saya, bahwa di sinilah kejeniusan Al‑Ghazali terlihat. Dia bukan cuma membela tasawuf dari kritik luar, tapi juga membersihkannya dari dalam. Tasawuf menurut Al-Ghazali tidak cukup hanya soal “rasa”, juga harus ada ilmu. Harus ada keseimbangan antara batin dan lahir. Hemat saya, pendekatan Al‑Ghazali ini yang mampu membawa tasawuf bisa diterima lebih luas, bahkan sampai jadi bagian pendidikan di pesantren dan kehidupan masyarakat umum, khususnya di Indonesia.
Sumber Referensi:
1. “Kontribusi Imam Al‑Ghazali terhadap Eksistensi Tasawuf” — Al‑Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu‑Ilmu Keislaman ( https://doaj.org/article)
2. Artikel “Perjalanan Imam Al‑Ghazali dari Filsuf menuju Tasawuf” oleh Edi Sumanto ( https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/twt/article )
3. “Sejarah Intelektual Islam di Bidang Tasawuf: Imam Al‑Ghazali, Ibnu Arabi, dan Mulla Shadra” ( https://www.journal.uiad.ac.id/index.php/al-qalam/article )
4. Kajian tentang “Maqamat Makrifat Hasan Al Basri dan Al‑Ghazali” ( https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article )