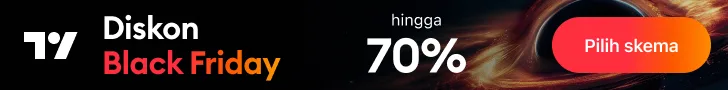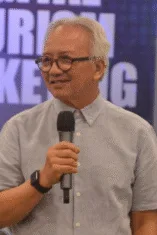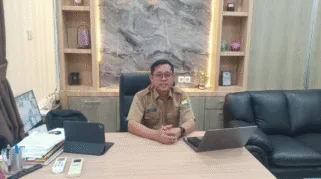Kemudian datanglah Al‑Ghazali (lahir 450 H /1057 M). Beliau semacam titik balik dalam sejarah tasawuf Islam. Kenapa? Karena pada zamannya banyak aliran yang mulai melebar kepada hal-hal yang dianggap menyimpang: panteisme, hulul (pemahaman bahwa Tuhan “turun” ke ciptaan secara literal), wahdatul wujud (bahwa wujud semua adalah Tuhan; yang lain hanya ilusi), dan penggabungan filsafat Yunani secara bebas. Beberapa ulama dan fuqaha mulai khawatir bahwa tasawuf akan kehilangan akar pribadinya dalam Qur’an dan Sunnah.
Al‑Ghazali kemudian mencoba “membenahi” tasawuf kemudian menariknya kembali ke Qur’an dan Sunnah, menggabungkan antara syari’at (aturan lahiriah) dengan tasawuf (dimensi batiniah), dan menyaring unsur‑filsafat yang dianggap terlalu spekulatif. Karya monumental beliau Ihya Ulum al‑Din adalah contoh bagaimana tasawuf tidak hanya buat orang‑orang mistik saja tapi bisa jadi bagian dari hidup orang sehari‑hari, moral, ibadah, sosial.
Setelah Al‑Ghazali, perkembangan dan dampak tasawuf sangat luas. Tasawuf yang moderat makin diterima di kalangan ulama syariat (ahlu sunna wa jama’ah). Kritik terhadap praktik yang dianggap menyimpang makin sering muncul. Tasawuf dianggap tidak boleh bertentangan dengan syari’at; karya‑karya sufi yang ekstrem atau yang menggunakan istilah mistis yang bisa disalahartikan mulai dikaji ulang atau dikoreksi.
Tokoh‑tokoh setelah Al‑Ghazali ikut mengambil jalan ini: mereka menyeimbangkan antara aspek moral, batin, dan hukum. Juga, pengaruh Al‑Ghazali terasa sangat kuat di banyak wilayah Islam termasuk Asia Tenggara, di pesantren, tarekat, pendidikan karakter. Tasawuf bukan cuma dihormati sebagai jalan mistik, tapi sebagai bagian resmi pendidikan Islam di beberapa wilayah.